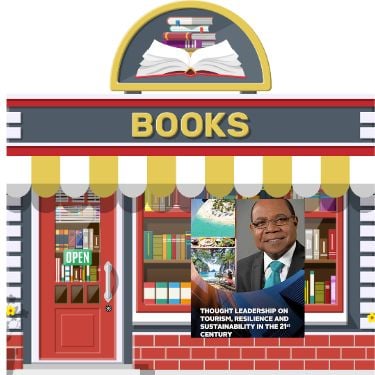Pada dini hari yang dingin di tempat yang menakjubkan dan dulunya terpencil ini, para backpacker Eropa yang lusuh dan turis Amerika yang kaya raya telah mengintai posisi tembak mereka.
Rangkaian kamera dan videocam yang berkedip-kedip, berdesak-desakan, dipicu saat para biksu Buddha berjalan tanpa alas kaki keluar dari biara mereka dalam ritual yang tenang dan abadi. Gelombang maju menerobos barisan jubah kuning keemasan, dan hampir menginjak-injak wanita Lao yang berlutut menawarkan makanan kepada para biarawan.
Kemudian pada hari itu, seorang pangeran dari bekas ibu kota kerajaan yang berjuang untuk melestarikan warisan budaya kotanya, memprotes: “Bagi banyak turis, datang ke Luang Prabang seperti pergi bersafari, tetapi biksu kami bukanlah monyet atau kerbau.”
Terletak jauh di lembah Sungai Mekong, terputus dari sebagian besar dunia oleh Perang Vietnam, Luang Prabang sangat berbeda ketika saya pertama kali melihatnya pada tahun 1974.
Berjumbai di tepinya, ya, tetapi masih merupakan perpaduan ajaib dari tempat tinggal tradisional Laos, arsitektur kolonial Prancis, dan lebih dari 30 biara anggun, beberapa berasal dari abad ke-14. Itu bukan museum, tapi komunitas hidup yang kohesif, otentik.
Maju cepat ke 2008: Banyak keluarga lama telah pergi, menjual atau menyewakan rumah mereka kepada orang luar kaya yang telah mengubahnya menjadi wisma tamu, kafe internet, dan kedai pizza. Ada lebih sedikit biksu karena pendatang baru tidak lagi mendukung vihara. Dan masuknya turis meroket, kota rapuh berpenduduk 25,000 sekarang menerima sekitar 300,000 dari mereka per tahun.
Di seluruh Laos, pariwisata meningkat secara mengejutkan sebesar 36.5 persen pada tahun 2007, dibandingkan tahun 2006, dengan lebih dari 1.3 juta pengunjung dalam 10 bulan pertama tahun ini, menurut Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik.
Beberapa waktu telah berlalu sejak destinasi di persimpangan utama Asia – Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan lain-lain – pertama kali menerima arus masuk ini, bahkan, ironisnya, saat mereka dibuldoser dan pencakar langit di atas karakter, atmosfer, dan sejarah yang menarik pengunjung. penerbangan jumbo.
Sekarang, giliran tempat-tempat yang pernah terisolasi oleh konflik, rezim yang bermusuhan, dan geografi "off-road" yang sebelumnya hanya dilalui oleh para pelancong yang lebih pemberani.
Dan sebagai permata kecil terakhir Asia, satu demi satu, menyerah pada dampak layu pariwisata, benar-benar ada rasa sakit di hati saya, bersama dengan dosis kecemburuan egois untuk cinta yang sekarang harus dibagikan kepada banyak orang.
“Siem Reap mungkin salah satu dari sedikit tempat yang masih melekat pada sisa-sisa Kamboja tua, sebelum perang, sebelum pembantaian,” tulis saya dalam buku harian saya pada tahun 1980, kembali ke kota barat laut Kamboja ini hanya beberapa bulan setelah jatuhnya Khmer Merah yang kejam.
Korban manusia sangat mengerikan, tetapi Siem Reap sendiri bertahan, skalanya yang kecil dan lesu, pasar Prancis kuno, suasana artistik yang begitu sesuai dengan komunitas di tepi kreasi terbesar Kamboja, kuil-kuil kuno Angkor.
Di Angkor Wat, sepasang suami istri tua yang tidak memiliki uang sepeser pun menawarkan jus gula aren hangat dari cangkir bambu ketika beberapa tentara mengawal saya, satu-satunya turis, melalui kamar-kamar yang menghantui kuil yang paling megah dari semuanya.
Pada kunjungan baru-baru ini ke Siem Reap, saya menemukan tempat kerja yang hiruk pikuk dan berdebu. Hotel bertingkat dengan jendela kaca bermunculan di tepi Sungai Siem Reap yang malas, di mana limbah mentah mengalir dari banyak wisma tamu. Pasar memiliki lebih banyak bar per blok daripada Las Vegas.
Orang-orang yang mengalami trauma spiritual sekarang dapat memesan sesi penyembuhan satu-satu di retret mewah dengan "pelatih kehidupan" yang diterbangkan dari Amerika Serikat, dan bungkus perut "Angkorean" dari daun teratai dan nasi hangat.
Para calon prajurit, karena kelelahan di kuil, melemparkan granat tangan dan menembakkan senapan serbu seharga $30 per ledakan di Lapangan Menembak Angkatan Darat. Resor Golf dan Spa Phokeethra Royal Angkor, yang menawarkan jembatan abad ke-11 antara lubang ke-9 dan ke-10, telah membawa “permainan tuan-tuan ke Keajaiban Dunia Kedelapan.”
Jalan sepanjang enam kilometer dari Siem Reap menuju keajaiban itu, dulunya merupakan gang yang tenang dengan deretan pepohonan yang menjulang tinggi, membentuk barisan hotel dan pusat perbelanjaan jelek seperti mal – kebanyakan melanggar undang-undang zonasi.
Pada malam terakhir saya, saya pikir Grand Prix sedang dijalankan. Pelancong muda berkumpul untuk pesta matahari terbenam sementara bus mengantarkan turis China ke jalan lintas besar Angkor Wat, yang diliputi oleh asap knalpot yang naik.
Mungkin kelompok paket dan wisatawan kelas atas, dengan tuntutan pemeliharaan yang tinggi, meninggalkan jejak yang lebih besar daripada backpacker. Namun di Asia, backpacker telah berperan sebagai tim pengintai industri, menembus pedalaman pedesaan untuk menjajah tempat-tempat indah dan membuka jalan bagi wisatawan kelas atas. Sirkuit panekuk pisang disebut, setelah salah satu kebutuhan pokok mereka.
Ambil contoh Pai, sebuah desa yang terletak di lembah luas yang dikelilingi gunung di Thailand utara. Dulunya merupakan pelarian besar ke dunia yang santai dan eksotis, dengan pemukiman suku yang tersebar di perbukitan, sampai suku migrasi global muncul berbondong-bondong, menyeret budayanya sendiri.
Pondok wisata bambu dan jerami memeluk Sungai Pai yang berkelok-kelok sejauh mata memandang, melahap sawah dan mendaki lereng bukit di tepi kirinya. Di tepi kanan, resor mahal mulai menjamur.
Jalur pusat kota yang pendek penuh dengan Apple Pai dan sembilan kafe internet lainnya, toko video dan tato, bar, kelas yoga dan memasak, toko perhiasan yang tak terhitung jumlahnya, dan restoran yang menyajikan bagel dan krim keju.
Bahkan ada surat kabar berbahasa Inggris, yang diterbitkan oleh Joe Cummings, seorang penulis Alkitab tentang perjalanan hemat, panduan Lonely Planet, yang mungkin melakukan lebih dari apa pun untuk menempatkan Pai di sirkuit. Dalam lamunan yang jahat, saya mengutuk Joe untuk tidak makan apa pun selain pancake pisang dan menyeret ransel seberat 500 pon sepanjang kekekalan.
Bahkan mereka yang mencari nafkah dari pariwisata menyayangkan pertumbuhan tersebut.
“Sekarang terlalu berkembang. Terlalu banyak beton di mana-mana, terlalu banyak wisma tamu,” kata Watcharee Boonyathammaraksa, yang, ketika saya pertama kali bertemu dengannya pada 1999, baru saja meninggalkan dunia periklanan Bangkok yang panik untuk memulai sebuah kafe, All About Coffee, di satu-satunya rumah kayu tua. tertinggal di kota.
Luang Prabang telah berbuat lebih baik dalam tidak meruntuhkan masa lalunya. UNESCO terus mengawasi setelah mendeklarasikannya sebagai situs Warisan Dunia pada tahun 1995. Badan tersebut menggambarkan permata perkotaan sebagai "kota yang paling terpelihara di Asia Tenggara."
Namun, mantan ahli dan penduduk UNESCO, Francis Engelmann, mengatakan: “Kami telah menyelamatkan bangunan Luang Prabang, tetapi kami telah kehilangan jiwanya.”
Komunitas tradisional bubar dalam kebangkitan pariwisata, dengan mereka yang mengambil alih tempat tinggal lama yang tertarik pada keuntungan daripada mendukung biara-biara, yang sebagian besar ada atas persembahan umat beriman.
Satu biara, kata Engelmann, telah ditutup dan kepala biara lain mengeluh bahwa turis masuk tanpa diundang ke tempat mereka untuk mengambil foto "tepat di hidung mereka" saat mereka belajar atau bermeditasi.
Pendeta senior melaporkan narkoba, seks, dan kejahatan ringan, yang dulu hampir tidak dikenal, di antara novis muda saat bujukan dan godaan impor berputar-putar di sekitar gerbang kuil mereka.
“Berkelanjutan, etis, ekowisata” – pejabat pariwisata di Laos dan di tempat lain di Asia melantunkan mantra modis ini. Tetapi rencana operasional mereka mendorong untuk "lebih, lebih, lebih."
Tidak ada yang menjerumuskan pemerintah dan pemasar kawasan itu ke dalam bahaya yang lebih dalam daripada penurunan kedatangan karena tsunami atau wabah flu burung.
Di Luang Prabang, menurut hitungan resmi, lebih dari 160 wisma dan hotel sudah beroperasi, dengan Cina dan Korea merencanakan beberapa yang sangat besar untuk perdagangan grosir.
Di sepanjang blok panjang Jalan Sisavangvong, di pusat kota tua, setiap bangunan melayani wisatawan dengan berbagai cara. Sungguh menyenangkan akhirnya menemukan satu yang tidak, bahkan jika itu adalah perumahan Federasi Serikat Buruh Provinsi Luang Prabang. Seorang lelaki tua kurus, bertelanjang kaki dan hanya mengenakan sarung kotak-kotak biru, akan menjadi pemandangan umum beberapa tahun yang lalu. Sekarang, saat dia berjalan melintasi Sisavangvong, di antara sepatu trekking dan parka mewah, dia tampak seperti orang asing di kampung halamannya sendiri.
Di dekatnya, di Rumah Budaya Puang Champ, teman saya Pangeran Nithakhong Tiaoksomsanith berharap untuk entah bagaimana bertindak sebagai saluran budaya asli Laos antara generasi yang mengglobal dan generasi yang lewat.
Rumah kayu tradisionalnya, yang disangga di atas panggung, berfungsi sebagai pusat di mana para empu tua mengajar musik, menari, memasak, menyulam benang emas, dan seni lainnya.
Ini, kata Nithakhong, dapat membantu mencegah kemungkinan nasib Luang Prabang: “Disneyland.”
Maka, pada sore hari, empat remaja di bawah bimbingan seorang musisi yang pernah tampil di istana kerajaan, berlatih. Pada string dan perkusi, mereka memainkan The Lao Full Moon, sebuah lagu romantis yang sedih.
Tetapi bahkan kompleks pribadi ini rentan. Saat anak-anak bermain, seorang turis mencoba menerobos masuk. Dan siapa itu di balik tembok, menjulurkan leher mereka?
Lebih banyak turis, mengklik kamera di tangan.
thewhig.com