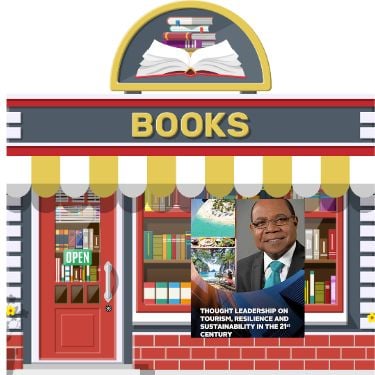Saat membaca artikel Michele Chabin “Umat Kristen Israel mencari integrasi, termasuk dinas militer” di USA Today, yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2014 – sebuah artikel yang berfokus pada keputusan umat Kristen tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dijalankan oleh negara Israel, mengenai tanggapan masyarakat yang berbeda terhadap hal tersebut. keputusan tersebut, dan mengenai perekrutan langsung orang-orang Kristen yang dilakukan oleh pemerintah Israel untuk menjadi tentara Israel dan badan-badan lainnya – saya berhenti pada tiga poin. Setiap poin mewakili kepalsuan besar, penafsiran yang keliru, kesalahpahaman, atau pengurangan; setiap poin membuka pintu ke topik yang belum dijelajahi dalam artikel Chabin, topik yang harus kita diskusikan untuk benar-benar memahami realitas umat Kristen di Israel dan Palestina.
Kata pertama yang membuat saya terdiam muncul dalam judulnya: integrasi dalam “Umat Kristen Israel mencari integrasi….” Penggunaan kata ini mengingatkan saya pada banyak imigran di Eropa yang kesulitan memahami marginalisasi mereka dalam konteks sosial baru dan seringkali menyalahkan diri mereka sendiri karenanya; yang tidak mereka lihat adalah kebijakan dan sikap yang menghalangi mereka untuk menjadi bagian integral dari masyarakat. Jadi, dalam kasus Israel, sebagian umat Kristen gagal melihat kebijakan, undang-undang, dan praktik diskriminatif terhadap warga negara non-Yahudi. (Ketegangan mendasar dari negara Israel sendiri – definisi negara Israel sebagai negara demokrasi dan negara Yahudi, keinginannya untuk menjadi model cita-cita demokrasi dan pada saat yang sama mereka juga bersikeras untuk mempertahankan mayoritas Yahudi – sering dijadikan referensi dan penting untuk diingat. Di Sini.)
Para korban diskriminasi sistematis ini sering kali memilih partai-partai paling sayap kanan di negara tuan rumah baru mereka – dengan berpikir, baik secara sadar atau tidak, bahwa menjadi anggota kelompok sayap kanan garis keras akan memberi mereka integrasi yang mereka dambakan. Dengan kata lain, mereka berusaha menjadi lebih Katolik daripada Paus. Dan apakah ini akan membantu mereka? Tentu saja tidak: mereka akan tetap menjadi “orang luar” di mata mayoritas, akan tetap tidak diinginkan, akan tetap menjadi “orang lain” yang ingin disingkirkan oleh kelompok sayap kanan. Ini adalah nasib yang sama yang dialami oleh warga negara non-Yahudi di negara Israel, meskipun pada kenyataannya mereka bukan imigran (dan, tentu saja, keluarga mereka telah menjalani kehidupan mereka dari generasi ke generasi), dan tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka adalah imigran. sebaliknya.
Poin kedua yang menarik perhatian saya adalah kutipan dari seorang pria Kristen Palestina yang bertugas di tentara Israel di kota Hebron – Saya akan menyebutnya “korban,” karena dia telah dirusak oleh sistem yang meminggirkan dia namun tetap mencuci otak. dia untuk mencari bentuk penerimaan ini. Korban ini harus menemani korban lainnya, seperti para rejectnik (warga muda Yahudi Israel yang menolak menjalankan wajib militer), yang melihat, misalnya, pemukim Yahudi di Hebron sebagai ancaman besar bagi negara Israel. Para pemukim ini bersikeras untuk tinggal di jantung komunitas Palestina, merampas akses air, penggunaan jalan-jalan, akses ke sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah bagi warga Palestina; melarang mereka melakukan kehidupan normal dengan berbagai cara; dan sering menyerang mereka secara fisik. Mereka berpendapat bahwa semua praktik ini berkontribusi terhadap keamanan negara Israel, dan mereka menganggap semua orang non-Yahudi sebagai orang luar yang harus dievakuasi dari negara “mereka”. Pembantaian Masjid Ibrahimi, yang dilakukan pada tahun 1994 oleh Baruch Goldstein, warga Israel kelahiran Amerika, hanyalah salah satu contoh dari mentalitas ini.
Keputusan korban untuk “melayani” para pemukim di Hebron, melindungi mereka di daerah kantong mereka, tidak akan mengubah opini mereka terhadap dirinya. Selain itu, keputusan Israel untuk menempatkan korban ini dan korban lainnya ke pos militer di Hebron merupakan keputusan yang tepat. Israel tidak mengirimnya ke perbatasan negara, atau ke Betlehem atau Ramallah, di mana ia bisa berhubungan dengan saudara-saudari Kristennya: menghentikan mereka di pos pemeriksaan, mempermalukan mereka di penghalang jalan, menangkap anak-anak mereka di tengah malam. . Kontak ini bisa saja membangkitkan beberapa perasaan tidak nyaman dan penting dalam dirinya: perasaan kebingungan, perasaan terhubung dengan orang-orang yang penindasannya dia kirimkan. Israel tidak ingin hal ini terjadi: tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan-hubungan tersebut, memecah-mecah komunitas, menghilangkan empati dan solidaritas jika hal ini mungkin timbul di kalangan warga Palestina dari berbagai latar belakang. Taktik memecah-belah ini semakin banyak muncul dalam undang-undang nasional: pada tanggal 24 Februari tahun ini, Knesset Israel mengesahkan undang-undang yang menciptakan perbedaan hukum antara umat Kristen dan Muslim, yang mengkategorikan umat Kristen sebagai non-Arab. Israel secara aktif berupaya membuat warga Palestina lupa bahwa mereka memiliki sejarah, komunitas, dan perjuangan yang sama. Satu-satunya cara para korban dapat “melindungi” negara mereka adalah dengan menolak menjadi instrumen pendudukan dan penindasan mereka sendiri.
Poin ketiga dan terakhir yang harus saya permasalahkan adalah kutipan dari penulisnya sendiri: “Orang-orang Kristen Pribumi mengatakan bahwa mereka dapat menelusuri asal usul mereka hingga 2,000 tahun yang lalu hingga zaman Yesus. Namun mereka mengeluh bahwa mereka kadang-kadang merasa seperti warga negara kelas dua di tanah air Yahudi dan tidak diberi pekerjaan dan jabatan penting di sektor swasta dan pemerintahan.” Mereka terkadang merasa seperti warga negara kelas dua? Penulis harus mengetahui, seperti yang diketahui oleh pengamat yang kompeten, bahwa warga negara Israel yang non-Yahudi berada pada peringkat warga negara kelas dua, tiga, atau empat. Dalam hierarki sosial di negara Israel, Yahudi Ashkenazi adalah kelas satu yang memiliki hak istimewa, diikuti oleh Yahudi Sephardic. (Kedua kategori ini tentu saja berisi sub-peringkat dan divisi lain, tetapi ini bukan topik teks saya.) Suku Druze, yang telah bertugas di ketentaraan dan “melindungi” negara mereka selama 50 tahun terakhir, menempati peringkat ketiga atau keempat; Terlepas dari pengabdian mereka, mereka terus-menerus mengalami diskriminasi dalam banyak konteks profesional dan sosial dan kota-kota mereka tidak mendapat alokasi anggaran seperti kota-kota Yahudi.
Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apakah mereka akan setara dengan orang-orang Yahudi di Israel? Akankah mereka dapat kembali ke desa tempat mereka diusir pada tahun 1948 dan beberapa tahun setelahnya? (Mari kita pikirkan desa Iqrit: pada tahun 1951, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penduduk desa dapat kembali dan menghuni rumah mereka. Namun pemerintah militer menemukan alasan untuk menolak mereka kembali, dan tentara Israel menghancurkan seluruh desa pada akhir tahun itu. ) Akankah Israel segera memiliki perdana menteri yang beragama Kristen? Atau presiden negara bagian? Sejarah, kebijakan, dan kenyataan merespons dengan jawaban “tidak” yang sangat besar. Populasi Israel adalah 20% non-Yahudi, selain ribuan orang Rusia, Asia, dan Afrika, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Namun wacana, kebijakan, dan praktik negara menekankan ke-Yahudi-an Israel di atas segalanya. Ia tidak tertarik pada kesetaraan. Dibutuhkan warga negara kelas dua untuk menjadi seperti sekarang ini.
Dalam situasi penindasan apa pun, sebagian dari mereka yang tertindas mengarahkan kemarahan mereka kepada para penindas. Namun ada juga yang tidak. Sebaliknya, mereka menyalurkan rasa frustrasinya kepada teman-temannya, sesamanya yang tertindas. Mereka mencoba menghapus masa lalu mereka, dengan harapan bahwa masa depan akan memberikan kehidupan yang lebih baik, sebuah kenyataan baru – dan sering kali, dalam prosesnya, mereka menjadi lebih rasis dibandingkan tetangga mereka yang paling fanatik. Meskipun demikian, sejarah mengingatkan kita bahwa proyeksi ini tidak akan pernah benar-benar membantu kaum tertindas. Para penindasnya akan terus memandang mereka sebagai orang asing – atau, paling banter, sebagai kelompok kelima, sebuah kelompok yang biasa melemahkan negaranya sendiri tanpa pernah mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang berusaha mengabdi pada mereka.