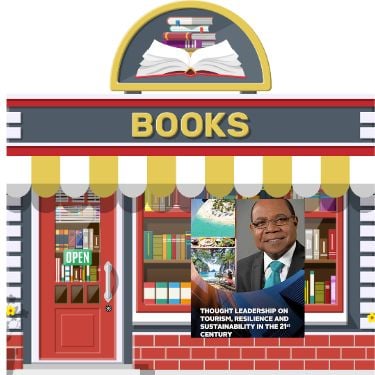Keanggunan yang luar biasa dan gerakan yang cermat dari para pemain telah memikat penonton sejak zaman kuno, sebuah pengalaman yang sekarang dibagikan dengan banyak turis yang turun di Siem Reap di Kamboja barat, titik awal untuk kompleks candi terbesar di dunia – Angkor Wat yang legendaris.
Kembali ke zaman kerajaan Angkor besar yang berkembang dari abad ke-9 hingga ke-15, tarian Kamboja adalah perayaan para dewa, mitologi, dan dunia istana kerajaan.
Buku setebal 144 halaman dengan ilustrasi mewah ini ditulis oleh Denise Heywood, seorang dosen seni Asia, membawa pembaca apresiasi yang bagus tentang tarian Kamboja yang terjalin dengan sejarah yang bergejolak dan bagaimana hal itu selalu menjadi inti budaya Khmer. dan identitas. Buku tersebut merinci dan menjelaskan asal-usul dan perkembangan tari, musik, dan wayang kulit, semua dalam konteks kepentingan spiritual mereka sebagai media untuk berkomunikasi dengan para dewa.
Tapi tragedi Kamboja baru-baru ini membawa tradisi tariannya yang hebat hampir terlupakan. Rezim “Lapangan Pembunuhan” Khmer Merah tidak hanya membunuh melalui kerja paksa, kelaparan, dan membantai hampir 2 juta orang, termasuk 90 persen seniman, penari, dan penulis, tetapi juga nyaris memadamkan budaya dan tradisi Khmer. Distopia agraria baru Pol Pot tidak memiliki tempat untuk seni, budaya, atau jenis hiburan lainnya kecuali lagu-lagu xenofobia dan propaganda Pol Pot.
Heywood pertama kali tiba di Kamboja sebagai penulis lepas pada tahun 1994, dan minatnya pada tari meningkat dengan kisah luar biasa tentang bagaimana beberapa penari dan koreografer selamat dari tahun-tahun genosida dari tahun 1975 hingga 79.
Pada bulan Januari 1979, pemerintahan baru Heng Samrin yang didukung oleh Vietnam memproklamirkan pemulihan masyarakat normal setelah empat tahun rezim Pol Pot telah menghancurkan sebagian besar aspek kehidupan keluarga dan masyarakat sebelumnya.
Segelintir orang yang selamat muncul dari era tergelap dalam sejarah Kamboja yang didedikasikan untuk menghidupkan kembali tradisi tarian mereka yang berharga. Aktor, penyair, dan sutradara Pich Tum Kravel dan mantan direktur National Conservatory Chheng Phon termasuk di antara bintang budaya yang secara ajaib selamat.
Mereka menjadi orang-orang kunci yang direkrut oleh Kementerian Informasi dan Kebudayaan yang baru di bawah Keo Chenda, yang ditugasi dengan misi penting untuk menyatukan semua penari yang masih hidup.
Keahlian itu diturunkan dari generasi ke generasi dari guru ke murid dan tidak pernah didokumentasikan dalam bentuk tertulis, jadi semuanya tergantung pada ingatan manusia. Almarhum Chea Samy menjadi guru terkemuka di Sekolah Seni Rupa yang didirikan kembali pada tahun 1981 (ironisnya Pol Pot adalah saudara iparnya).
Menyatukan kenangan kolektif para penyintas dan sebagian besar perbendaharaan yang luas, seni pertunjukan dihidupkan kembali.
Ketika pengulas ini melihat Perusahaan Tari Nasional Kamboja pasca-Pol Pot tampil di Phnom Penh pada tahun 1981, itu adalah pengalaman yang sangat emosional. Para penonton menangis. Pencurahan emosi mentah ini meliputi air mata kesedihan bagi orang-orang terkasih yang tidak akan pernah mereka lihat lagi – dan air mata kegembiraan karena tarian Khmer hidup kembali dan telah bangkit dari abu kehancuran nihilistik.
Tidak ada yang lebih penting bagi orang Khmer dalam proses pembangunan kembali ini selain kebangkitan jiwa dan jiwa bangsa di mana tarian memainkan peran sentral.
Sementara Heywood dipuji karena dokumentasinya tentang kebangkitan tari pada 1980-an, sangat disayangkan dia salah mengontekstualisasikan kebangkitan budaya ini dengan mengklaim bahwa "pemerintah Vietnam Heng Samrin" menyelenggarakan festival seni nasional pada 1980.
Faktanya, Presiden Heng Samrin dan semua orang di pemerintahan baru semuanya adalah orang Kamboja dan bukan orang Vietnam. Entah bagaimana penulis telah terinfeksi dengan propaganda perang dingin yang berasal dari pemerintah Asean dan kedutaan besar AS di wilayah tersebut.
Kenyataannya lebih rumit. Kebangkitan budaya yang digambarkan dalam buku ini memperjelas bahwa kontrol Vietnam atas keamanan dan kebijakan luar negeri, terlepas dari ketegangan dan perbedaan dengan sekutu Kamboja mereka, tidak menghalangi munculnya kembali budaya Khmer yang pada saat yang sama menanam benih untuk kemerdekaan masa depan.
Pada tahun 2003, Unesco menganugerahkan pengakuan formal yang menyatakan Balet Kerajaan Kamboja sebagai mahakarya warisan lisan dan takbenda. Dan satu tahun kemudian, Pangeran Norodom Sihamoni, mantan koreografer dan penari balet, dinobatkan sebagai raja.
Tarian klasik Thailand banyak meminjam dari tradisi tari zaman Angkorian. Setelah invasi Siam ke Siem Reap pada tahun 1431, ratusan penari Kamboja diculik dan dibawa untuk menari di Ayutthaya, yang saat itu menjadi ibu kota istana raja Thailand.
Buku yang tepat waktu ini juga menyebutkan bahwa koreografer Kamboja Sophiline Shapiro telah, di antara banyak proyek lainnya, mengadaptasi Suling Ajaib Mozart ke tarian klasik Khmer sebagai bagian dari festival 2006 untuk memperingati 250 tahun kelahiran komposer hebat.
Produksi dengan banyak inovasi ini menyebabkan kegemparan di antara kaum puritan. Shapiro dengan penuh semangat membela produksi barunya melawan para kritikus, dengan mengatakan kepada penulisnya, “meningkatkan perbendaharaan tari akan membantu melestarikannya dan mencegahnya berhenti berkembang atau menjadi bagian museum.”